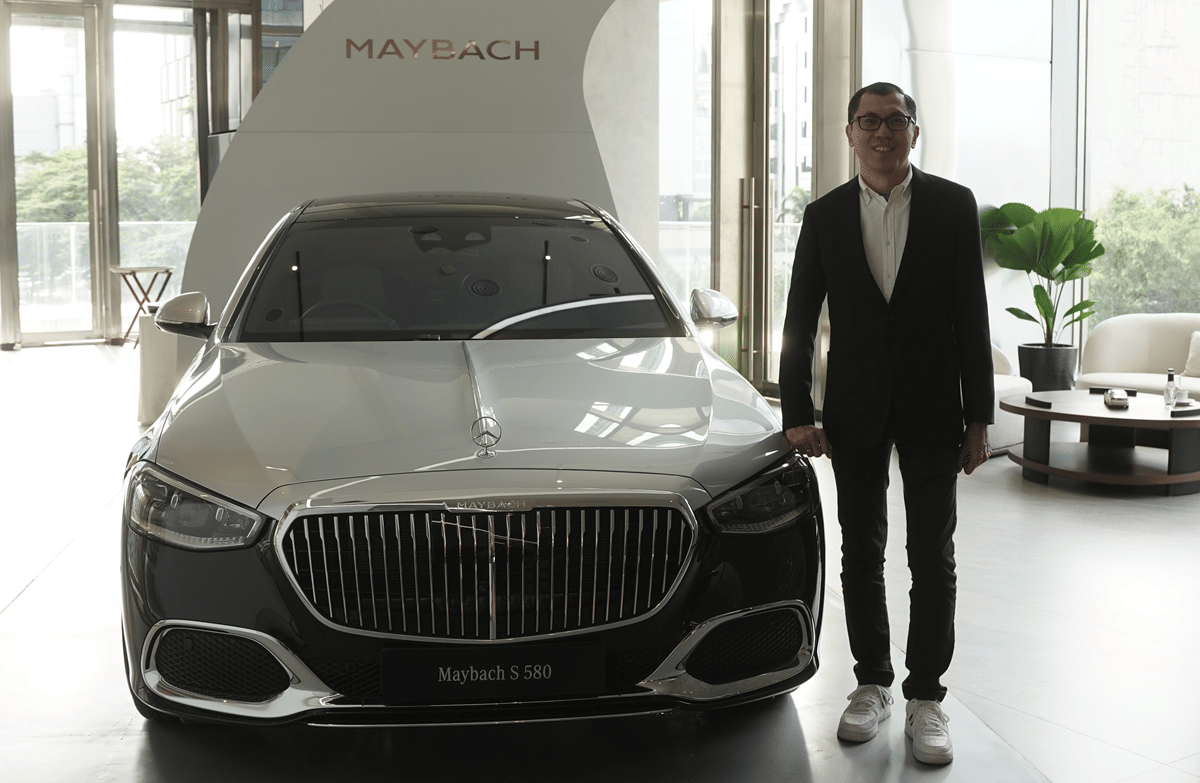Efek Domino Tarif Trump bagi Industri Mode

Jakarta, FORTUNE - Perang dagang yang kembali digencarkan oleh mantan Presiden Donald Trump terhadap Cina menimbulkan kekhawatiran besar di sektor mode global. Bukan hanya industri fast fashion yang akan terdampak, tetapi juga merek-merek mewah hingga manufaktur kasmir kelas atas.
Data dari Biro Sensus AS menunjukkan bahwa pada 2023, Amerika Serikat mengimpor pakaian dan tekstil senilai US$19,6 miliar dari Cina. Peningkatan tarif impor diperkirakan memicu efek domino di seluruh rantai pasok industri mode.
“Salah kaprah yang umum adalah bahwa Cina hanya memproduksi barang murah, dan jika diputus, kita akan beralih ke pakaian kelas atas. Padahal mereka memproduksi dari kaus Shein seharga US$5 hingga sweater kasmir Double RL US$1.200," kata Derek Guy, pemerhati mode pria, mengutip Busines Insider (22/4).
“Mereka tidak pakai pabrik Cina karena mau beli cardigan US$2. Tapi karena pabrik itu membuat cardigan terbaik dengan gaya tersebut,” katanya, menambahkan.
Meski sebagian produksi telah dipindahkan ke negara seperti Vietnam dan Kamboja, pakar sejarah seni Anne Higonnet menyebut bahwa tarif baru tetap bisa menjadi “pukulan terbesar” bagi industri mode cepat.
“Perusahaan tidak bisa begitu saja membangun pabrik di AS dan mempertahankan harga lama,” ujarnya.
Tarif tambahan ini membuat perusahaan berada di persimpangan sulit: menaikkan harga atau menurunkan kualitas. Hal ini bisa memicu perubahan besar dalam perilaku konsumen. “Kalau situasinya terus seperti ini, kita akan terus mengenakan pakaian warna krem," kata Dana Thomas, penulis Deluxe: How Luxury Lost Its Luster.
Resesi mode dan dampak psikologi konsumen
Efek ekonomi dari kebijakan perdagangan ini semakin memperbesar bayang-bayang resesi. Dan dalam setiap ketidakpastian ekonomi, dunia fashion menunjukkan pola yang berulang: gaya kembali pada yang dasar dan fungsional.
“Resesi cenderung meredam aspirasi. Ketika masa depan terasa tidak pasti, mode cenderung kembali pada hal yang familiar," kata Sarah Owen, pengamat tren dan ilmuwan sosial.
Sejarah mencatat hal serupa dalam Depresi Besar, resesi dot-com, hingga krisis finansial 2008. “Dalam resesi masa lalu, tren mode menjadi lebih tenang,” kata Monisha Klar dari WGSN.
Vincent Quan dari Fashion Institute of Technology menambahkan bahwa warna netral seperti hitam, putih, dan abu-abu mendominasi saat krisis. “Penekanan. Desain yang kurang berani. Kebangkitan gaya lama alih-alih sesuatu yang benar-benar baru,” kata Higonnet.
Dalam bayang-bayang tarif dan ketidakpastian ekonomi, tren quiet luxury dan busana dasar tetap bertahan. Walau masyarakat kelas atas tetap berbelanja, gaya mereka menyesuaikan dengan sensitivitas sosial.
“Waktu itu dianggap tidak pantas untuk memamerkan kekayaan karena banyak orang kehilangan harta,” ujar Thomas, merujuk pada pasca-2008.
LVMH dan Hermès menunjukkan tanda-tanda tekanan pasar, dengan Hermès menaikkan harga di AS sebagai respons terhadap potensi tarif lanjutan. “Kemewahan tidak akan pernah hilang, hanya menjadi lebih tenang,” kata Owen.
Konsumen umum pun mengarah ke gaya yang praktis dan hemat. "Akan ada pergeseran menuju nilai guna,” kata Quan. Ke depannya diprediksi, akan ada peralihan mendadak dari ide-ide maksimalis.
Pasar barang bekas akan tumbuh, tetapi merek mewah kelas menengah justru berada dalam posisi paling rentan. “Merek mewah kelas menengah selalu menjadi yang pertama merasakan tekanan. Tidak cukup esensial ataupun mencerminkan status untuk tetap dibeli,” ujar Owen.