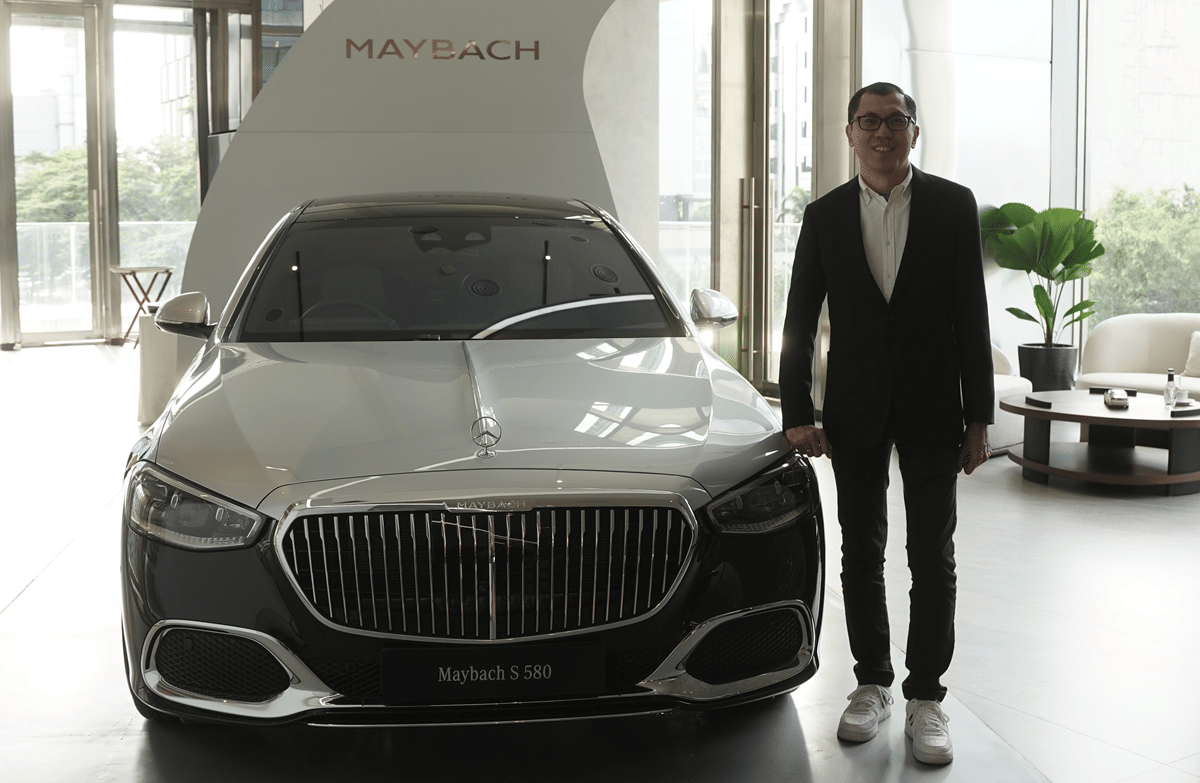Dari Koper ke Sendok: Perjalanan Louis Vuitton dalam Meracik Rasa

Jakarta, FORTUNE - Di balik koper kulit yang menjelajah dunia, di antara jahitan monogram yang tak lekang oleh zaman, Louis Vuitton menyimpan hasrat lain—yang tak terdengar berderak di lintasan roda, tapi berdenting pelan di meja makan.
Suatu pagi di Osaka, Februari 2020, ketika matahari menyentuh atap butik Louis Vuitton, sebuah pintu dibuka menuju dunia baru: bukan ruang ganti, bukan toko, melainkan sebuah restoran. Le Café V dan Sugalabo V—dua nama yang menandai awal dari sebuah babak baru bagi rumah mode yang lahir dari perjalanan. Kali ini, bukan koper yang dibawa, melainkan rasa.
Louis Vuitton sedang menulis ulang bahasa kemewahan. Ia tidak lagi dijual dalam bentuk tas tangan atau kacamata hitam, tapi dihidangkan dalam bentuk ravioli berukir monogram, cokelat berbentuk tas mini, dan tomat marmer yang dipotong setipis sutra. Dunia ini bukan hanya tentang apa yang dikenakan, tapi juga tentang apa yang dikecap dan dikenang.
Di Saint-Tropez, kota kecil yang dulu hanya ramai di musim panas, lahirlah Louis Vuitton Culinary Community atau komunitas kuliner Louis Vuitton—gagasan yang diracik oleh dua tangan ahli: Arnaud Donckele, koki yang tahu bagaimana menyeimbangkan keheningan dalam kaldu, dan Maxime Frédéric, pembuat manis yang memperlakukan cokelat seperti wasiat keluarga.
Mereka tak sekadar membuat restoran. Mereka membangun jaringan rasa, dari Bangkok hingga Chengdu, dari Doha ke New York, yang disatukan bukan oleh resep, melainkan oleh filosofi: menghadirkan keanggunan dalam suapan, bukan hanya tampilan. “Kami ingin pengalaman kuliner Louis Vuitton terasa santai,” ujar Donckele, dalam keterangannya (20/5).
Frédéric menambahkan, “Kami mendorong para koki untuk berkembang, tapi tetap dalam semangat Louis Vuitton.”
Dan semangat itu hidup di Saint-Tropez, di halaman hotel White 1921, tempat restoran mereka kembali membuka musim hingga September 2025. Di sanalah pohon pinus melindungi meja makan dari silau matahari, dan aroma lobster panggang dengan saus shiso berputar lembut bersama angin. Ada ikan sole dengan rempah lokal, ada vacherin rhubarb yang disajikan seolah waktu bisa berhenti sejenak di sore hari. Dan di setiap piring, warisan itu berbicara—bukan lewat kata-kata, tapi rasa.
Rasa yang tak pernah dijahit, tapi diciptakan

Estetika tetap menjadi narasi penting bagi Louis Vuitton dalam menorehkan jejak di ranah kuliner dunia. Taplak meja bersulam motif bunga dari koleksi Resort 2025, piring porselen Limoges putih susu dengan monogram yang ditata seperti puisi. Lampu rotan bergantung rendah, menciptakan suasana yang seperti ditarik dari album liburan Côte d’Azur era 70-an, lalu diberi sentuhan baru oleh tangan-tangan kontemporer.
Saint-Tropez bukan satu-satunya panggung bagi rumah modemewah ini. Di Paris, kafe Maxime Frédéric at Louis Vuitton menyuguhkan pastri segar di bawah naungan tropis dalam ruang pamer LV DREAM. Di New York, sebuah loteng butik di 57th Street berubah menjadi perpustakaan rasa—lobster roll khas Manhattan berdampingan dengan ravioli yang dicetak seperti dompet. Di Milan, Da Vittorio membawa semangat Italia dalam versi Vuitton. Di Heathrow, London, chef Cyril Lignac menciptakan pengalaman sebelum keberangkatan yang terasa seperti masih di rumah.
Dan di Timur, keindahan itu terus meluas. Di Tokyo, chef Yosuke Suga menyuguhkan keheningan Jepang dalam format rasa. Di Chengdu, Louis Vuitton mengajak lidah menjelajahi Eropa yang dibumbui Sichuan, dan Michelin pun memberi bintang. Di Doha, lounge di Bandara Hamad menjadi oasis sunyi di tengah keramaian bandara, dengan sajian 24 jam dari Yannick Alléno. Di Bangkok, Gaggan Anand—si pemberontak rasa—menyulam cerita Thailand dalam format haute cuisine, dengan napas Louis Vuitton di tiap napkin-nya.
Yang sedang dibangun Louis Vuitton bukan sekadar restoran. Ia tengah menciptakan sebuah peta baru—di mana titik-titiknya bukan ditandai oleh kota, tetapi oleh rasa. Dan dari rasa itu, kita dibimbing mengenal kemewahan yang lebih dalam, lebih personal, dan lebih halus. Kemewahan yang tak hanya terlihat, tapi terasa.
Belum ada laporan mendetail yang membedah seberapa besar porsi kuliner dalam neraca Louis Vuitton, tapi jejaknya terasa di tempat-tempat paling strategis yang menjelma menjadi perpustakaan rasa di berbagai belahan dunia. Louis Vuitton tahu, kemewahan hari ini bukan hanya soal kepemilikan, tetapi pengalaman. Sebab rasa, seperti halnya warisan, akan selalu tinggal lebih lama dari tren.