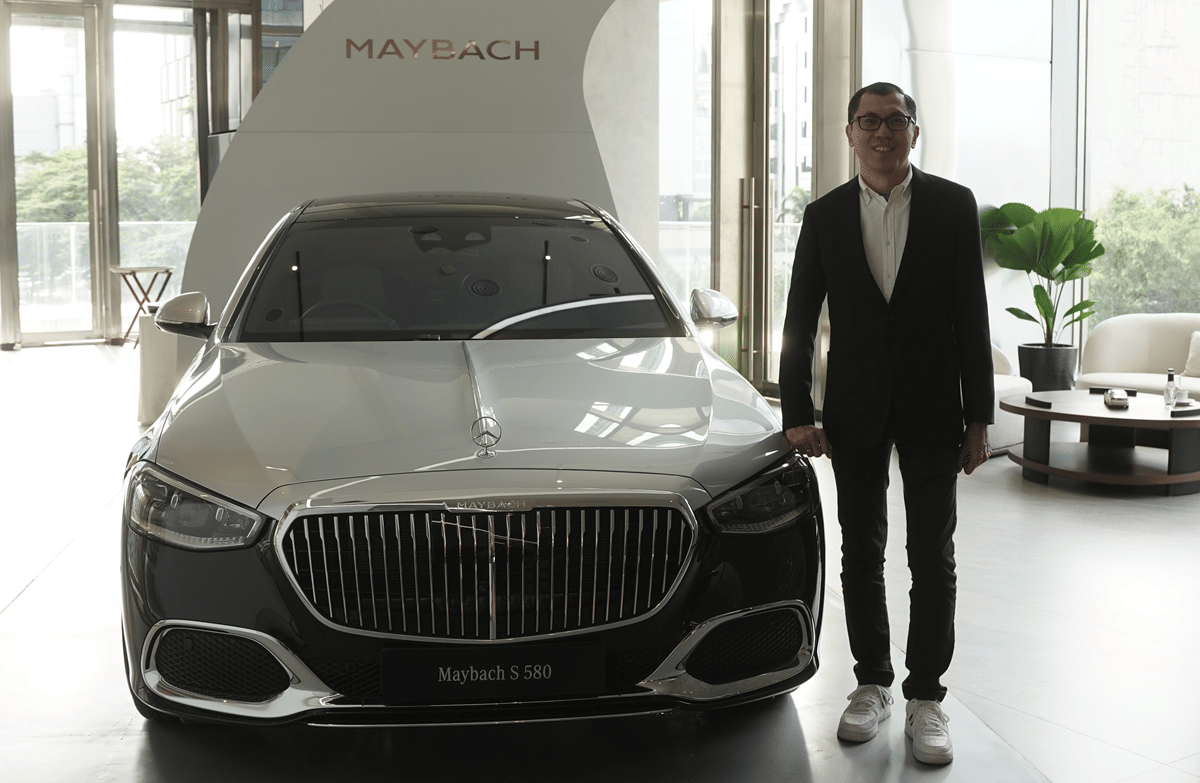Fesyen Berkelanjutan Tumbuh di Asia Tenggara, Bagaimana di Indonesia?

Jakarta, FORTUNE - Generasi pembeli baru di Asia Tenggara mendorong perubahan besar dalam industri fesyen. Kini, konsumen semakin memprioritaskan etika dibandingkan produksi massal, mendorong para desainer di kawasan ini untuk menjawab tuntutan akan mode berkelanjutan.
Selama ini dikenal sebagai pusat manufaktur fesyen cepat (fast fashion), Asia Tenggara kini bergeser dari fokus pada kuantitas ke nilai keberlanjutan. Di Singapura, pasar barang mewah dimanfaatkan untuk mendorong inovasi ramah lingkungan. Sementara itu, di Thailand, merek-merek independen menghidupkan kembali kerajinan lokal melalui pendekatan slow fashion.
Menurut laporan Thai Cyclopaedia tahun 2024, industri tekstil global menyumbang hingga 10 persen dari emisi karbon dunia dan 20% dari limbah air. “Konsumen kini bertanya dari mana dan bagaimana pakaian mereka dibuat,” ujar Allie Cameron, pendiri merek pakaian dalam berkelanjutan Hara, mengutip Jing Daily (27/5)
Berbeda dari negara produsen besar lainnya, Singapura membangun reputasi sebagai pusat fesyen mewah dan inovatif. Pemerintah dan lembaga industri seperti Singapore Fashion Council aktif membentuk ekosistem fesyen yang lebih hijau. Program seperti Fashion Sustainability Programme dan Zero Fashion Waste Initiative mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan solusi dari hulu ke hilir.
Data Badan Lingkungan Nasional Singapura mencatat produksi limbah tekstil dan kulit mencapai 211.000 ton pada 2023, namun hanya 2 persen yang didaur ulang. Meski begitu, proyeksi nilai industri fesyen negara ini diperkirakan mencapai US$2,5 miliar pada 2027.
Tren konsumsi pun berubah. Sebanyak 60 persen warga Singapura kini memilih merek berkelanjutan. “Konsumen muda memimpin perubahan ini. Mereka menghargai kejujuran dan etika, tak hanya estetika,” kata Kimberley Tan, pendiri label loungewear ramah lingkungan The Mori Club.
Menghidupkan kain tradisional
Thailand, dengan warisan tekstilnya yang kaya, juga turut bertransformasi. Merek-merek seperti Folkcharm, Sasi Knits, dan Mae Teeta bekerja langsung dengan perajin desa untuk memproduksi koleksi terbatas yang mengedepankan bahan alami dan teknik tradisional seperti pewarnaan indigo dan tenun kapuk.
Alih-alih memproduksi massal di pabrik besar, mereka memilih berakar di komunitas lokal, membayar upah layak, dan melestarikan keterampilan yang hampir punah. Sebuah studi di Bangkok mengungkap bahwa pengetahuan lingkungan dan persepsi terhadap kebijakan pemerintah mendorong minat milenial terhadap produk fesyen sirkular.
Di tengah kritik terhadap merek global seperti Shein dan Zara karena praktik greenwashing, merek-merek slow fashion Asia Tenggara menonjol berkat keterbukaan dan etika. Mereka membagikan proses produksi secara transparan, memperkenalkan penjahit atau pengrajin mereka, dan menjelaskan sumber serta biaya bahan. “Fast fashion memang menawarkan keterjangkauan dan kecepatan, tapi kami menawarkan koneksi yang lebih dalam dengan produk dan pembuatnya,” ujar Tan.
Sementara label “Made in China” atau “Made in Bangladesh” sering diasosiasikan dengan produksi massal, Asia Tenggara membangun identitas sendiri yang mengutamakan kreativitas desain dan tanggung jawab sosial. Produksi dalam skala kecil memungkinkan pengawasan ketat, termasuk pemanfaatan limbah kain menjadi produk baru seperti scrunchie atau aksesori.
Bagaimana di Indonesia? Industri fesyen berkelanjutan di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, didorong oleh meningkatnya kesadaran konsumen terhadap dampak lingkungan dan sosial dari industri mode. Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (MenEkraf/KaBekraf) Teuku Riefky Harsya mengatakan fesyen merupakan salah satu subsektor ekonomi kreatif yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB nasional. Akan tetapi, di sisi lain juga menyebabkan tingginya limbah yang dihasilkan dari industri ini, sehingga sudah saatnya menerapkan sustainable fashion.
"Fakta ini perlu disikapi dengan langkah bijak dan strategis yang salah satunya upaya menekan produksi limbah dengan upcycle produk fesyen atau fesyen yang berkelanjutan (sustainable fashion)," ujarnya, dalam keterangan pers. Berdasarkan data, subsektor fesyen berkontribusi terhadap PDB negara hingga 55 persen. Dari 33 juga ton tekstil yang diproduksi di Indonesia, kurang lebih 1 juta ton tekstil berakhir menjadi limbah.
Tren ekonomi ke depan
Mendorong penerapan gaya hidup sustainable lifestyle yang diyakini juga akan menjadi tren ekonomi kreatif ke depan. Sejumlah jenama lokal menerapkan prinsip fesyen berkelanjutan, di antaranya SukkhaCita yang didirikan pada 2016 yang memberdayakan pengrajin lokal dan menggunakan pewarna alami dalam produksinya. Merek ini juga berupaya mengurangi limbah tekstil dengan memanfaatkan sisa kain.
Kemudian ada Pijak Bumi jenama asal Bandung yang memproduksi alas kaki dari bahan daur ulang seperti kulit kelapa dan ban bekas, serta katun organik. Ada pula Sejauh Mata Memandang yang menggunakan bahan seperti katun, linen, dan tencel, serta menerapkan prinsip sirkularitas dengan memanfaatkan tekstil daur ulang dari limbah pra-konsumsi.
Asia-Pasifik kini menguasai 33 persen pasar fesyen etis global. Menurut proyeksi GMI, pasar pakaian berkelanjutan di Asia akan tumbuh hampir tiga kali lipat, dari US$3,9 miliar pada 2025 menjadi US$9,4 miliar pada 2034. Negara-negara Asia Tenggara diprediksi akan mengambil porsi besar dari pertumbuhan itu.
Dengan akar budaya kuat dan tradisi menghargai alam, Asia Tenggara memiliki fondasi otentik untuk memimpin transformasi fesyen dunia. Asia Tenggara tidak lagi sekadar latar belakang industri fesyen global — kini, kawasan ini menunjukkan kepada dunia bagaimana masa depan fesyen yang etis, elegan, dan berkelanjutan bisa terwujud.